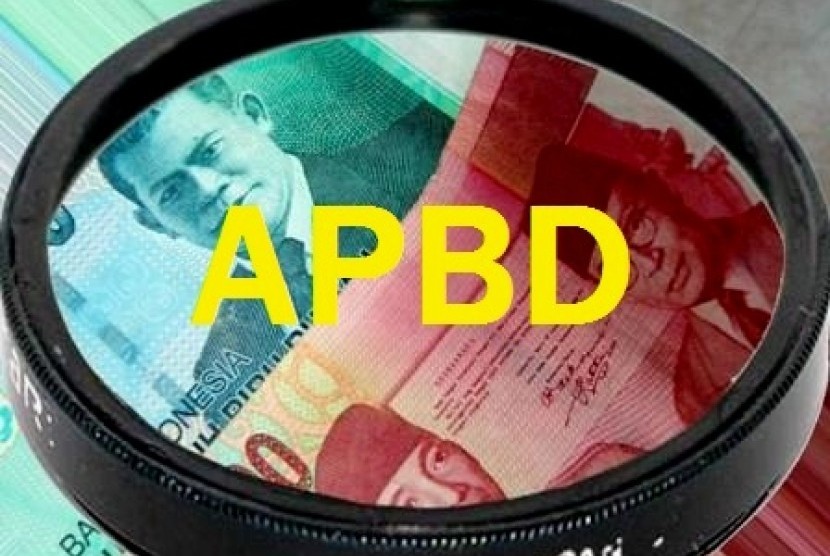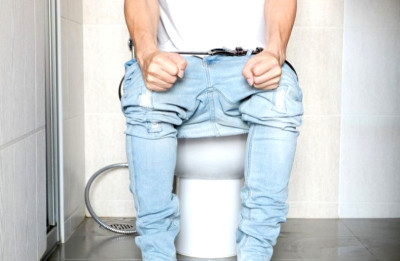Oleh : Ady Amar, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID,
“Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, keadilan mati di tangan penegaknya.”
— Yap Thiam Hien (1913–1989), pejuang hak asasi manusia dan advokat yang dikenal karena keberanian moralnya melawan penyalahgunaan hukum.
Negeri ini kembali menulis bab baru dari absurditas hukum: ketika bertanya dianggap bersalah, dan meneliti dijadikan tindak pidana. Polisi resmi menetapkan Roy Suryo, dr. Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar —bersama lima orang lain— sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Dalam konstruksi hukum yang dipakai penyidik, mempertanyakan keaslian ijazah kepala negara dianggap pelanggaran serius yang mencederai wibawa negara. Namun jika ditelusuri lebih dalam, tampak dua logika besar yang kini bertabrakan. Logika kekuasaan yang menutup perdebatan, dan logika publik yang menuntut transparansi.
Polda Metro Jaya mengklaim telah memeriksa lebih dari 130 saksi dan 20 ahli, serta melakukan pemeriksaan forensik yang hasilnya menyatakan ijazah Jokowi asli dan sah. Dengan dasar itu, polisi menyimpulkan dua hal: pertama, para tersangka diduga menyebarkan tudingan palsu yang mencemarkan nama baik presiden; kedua, sebagian di antaranya diduga memanipulasi data digital untuk memperkuat narasi tersebut.
Dari sana lahir pasal-pasal berlapis: fitnah (Pasal 310–311 KUHP), penyebaran berita bohong (Pasal 28 UU ITE), hingga manipulasi data elektronik (Pasal 32 UU ITE). Delapan orang itu kemudian dibagi dua klaster: klaster I yang disebut menyebarkan tudingan, dan klaster II —yang berisi Roy Suryo, dr. Tifauziah Tyassuma, serta Rismon Hasiholan Sianipar— yang dituduh melakukan analisis atau manipulasi digital terhadap dokumen ijazah.
Logika yang tumbuh dari konstruksi ini sederhana tapi berbahaya. Seolah negara menetapkan kebenaran, dan siapa pun yang mempertanyakannya dianggap bersalah. Pertanyaan bukan lagi jalan menuju kebenaran, melainkan ancaman terhadap stabilitas.
Roy Suryo dan rekan-rekannya menolak tuduhan itu. Mereka menegaskan apa yang dilakukan hanyalah penelitian atas dokumen publik —bentuk partisipasi warga dalam menilai keabsahan informasi negara. Dalam pandangan mereka, itu bukan kejahatan, melainkan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi publik.
Roy menegaskan tak ada niat mencemarkan nama baik. Ia hanya melakukan analisis terhadap dokumen yang beredar, seperti perbandingan visual dan penelaahan administratif. Begitu pula dr. Tifauziah Tyassuma —aktivis kesehatan dan pemerhati sosial— menyebut diskursus soal ijazah Jokowi dilakukan di ruang publik, dalam konteks akademik dan kebebasan berpendapat, bukan serangan personal.
Rismon Hasiholan Sianipar, yang juga termasuk dalam klaster II, menyatakan yang ia lakukan hanyalah menyampaikan argumen dan pertanyaan, bukan tudingan kriminal. Niat mereka, dengan demikian, bukan untuk merusak nama presiden, melainkan untuk menguji transparansi negara. Dan itu semestinya dilindungi, bukan dikriminalisasi.
Dalam kerangka hukum yang rasional, unsur niat jahat (mens rea) adalah hal utama. Pasal 310–311 KUHP menuntut pembuktian bahwa pelaku memang sengaja mencemarkan nama baik.
Tetapi bagaimana membuktikan niat jahat dari seseorang yang melakukan kajian terhadap dokumen publik? Tanpa pembuktian niat, penetapan tersangka menjadi rapuh dan mudah gugur di pengadilan.
Lebih jauh, hasil forensik yang dijadikan dasar penetapan tersangka belum pernah dipublikasikan secara utuh. Metode, sampel, dan nama ahli yang digunakan tidak diketahui publik. Bagaimana masyarakat dapat percaya pada kesimpulan “ijazah asli” bila bukti dan prosesnya tak transparan?
Ketertutupan semacam ini justru menimbulkan ruang spekulasi yang hendak mereka bungkam dengan cara represif. Padahal, transparansi adalah obat dari hoaks, bukan pasal pidana.
Jika logika hukum dijalankan dengan jernih, mestinya yang diuji lebih dulu adalah niat dan alat bukti. Bila tak ada data digital yang dimanipulasi dan tidak terbukti ada niat mencemarkan, maka unsur pidana tak terpenuhi. Namun aparat tampak memulai dari ujung: menetapkan tersangka lebih dulu, baru kemudian mencari bukti pendukung.
Hukum akhirnya bukan lagi pagar rasionalitas, melainkan alat menjaga kehormatan simbolik penguasa. Dalam negara demokrasi, martabat pejabat publik tidak dijaga oleh pasal pidana, melainkan oleh keterbukaan terhadap kritik.
Apa yang menimpa Roy Suryo, dr. Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Hasiholan Sianipar -- bersama lima orang lainnya: Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis — bukan sekadar perkara hukum. Delapan nama itu terbagi dalam dua klaster: klaster pertama dituduh menyebarkan tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, sementara klaster kedua — yang berisi Roy, dr. Tifa, dan Rismon — dituduh melakukan analisis atau manipulasi digital terhadap dokumen ijazah.
Namun di luar pembagian itu, kasus ini sejatinya adalah cermin dari politik hukum yang kian alergi terhadap sikap kritis. Sebuah potret negara yang makin takut pada cermin, karena bayangan yang muncul tak lagi memantulkan wajah kekuasaan yang ingin mereka lihat.
Kasus ini bukan sekadar soal ijazah, tetapi soal arah bangsa, apakah kita masih berani mempertanyakan kebenaran versi negara, atau memilih diam dalam kepalsuan yang dilembagakan? Roy Suryo cs mungkin bukan tanpa cela, tetapi menghukum rasa ingin tahu adalah kemunduran peradaban. Negeri ini tidak akan runtuh hanya karena warga meneliti selembar ijazah; namun ia bisa benar-benar hancur jika hukum dipakai untuk membungkam akal sehat. Jika bertanya saja dianggap kriminal, maka bukan hanya Roy Suryo yang diadili — melainkan seluruh nurani bangsa ini.

 2 hours ago
1
2 hours ago
1