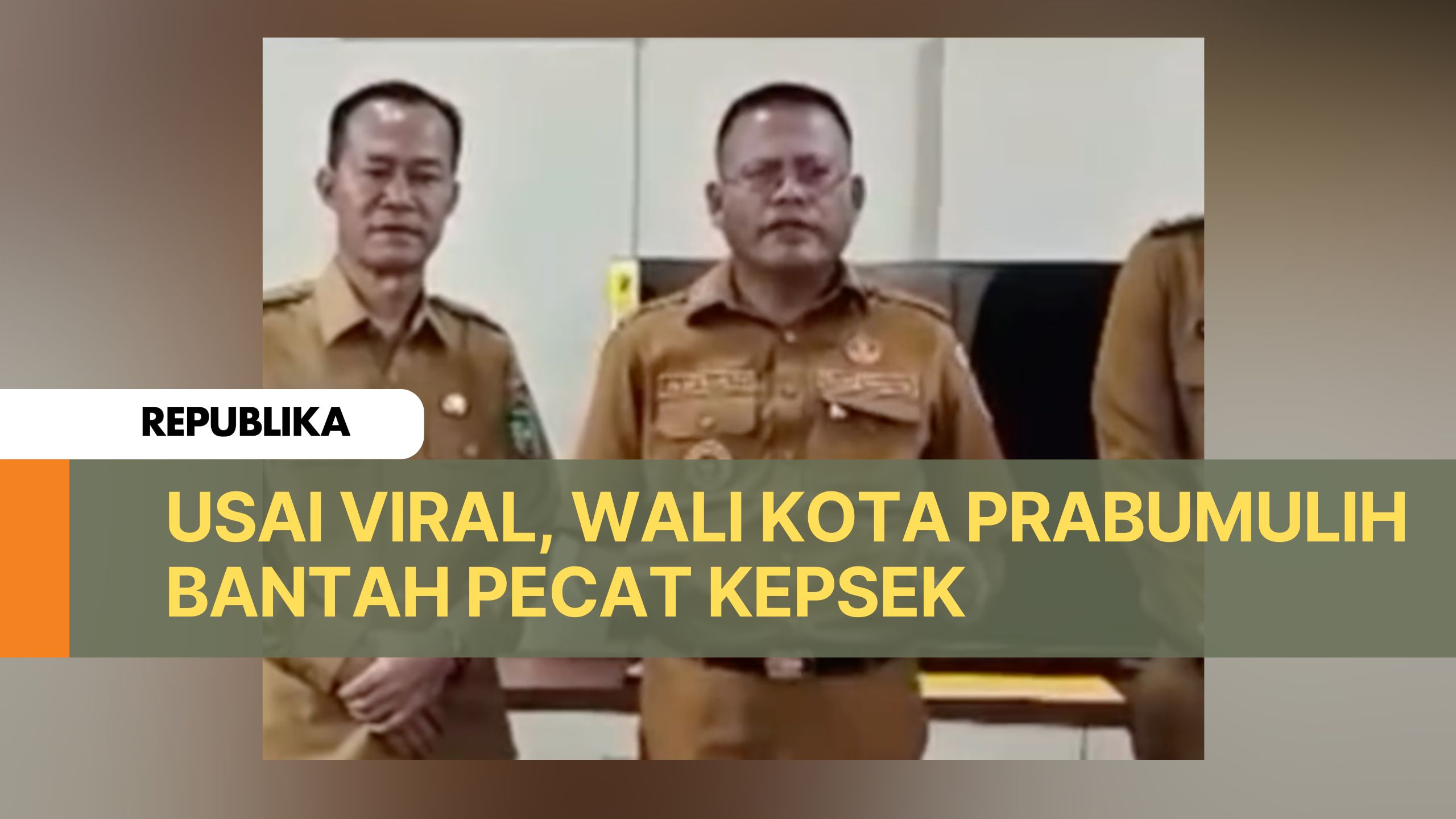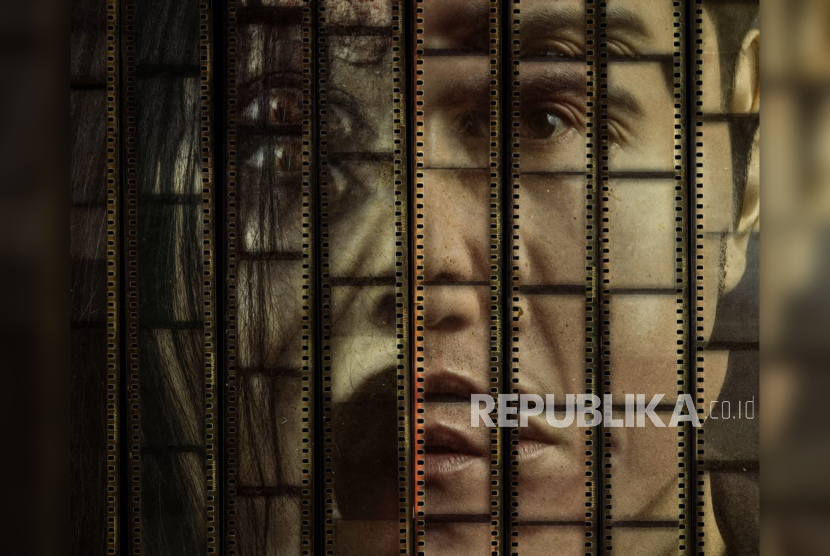Oleh : Aslichan Burhan, Direktur PINBUK ICMI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru Indonesia dengan fase kerja yang menuntut kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil keputusan.. Saya memandang arah yang dibawa Purbaya bukan sekadar deretan program, melainkan orkestra kebijakan—fiskal, perizinan, pembiayaan, dan perlindungan sosial—yang dimainkan serempak agar manfaatnya terasa sampai ke dapur rumah tangga, ke bengkel dan warung, petani, hingga ke kebun dan tambak.
Pola ini mengingatkan kita pada pelajaran besar era Presiden B.J. Habibie: ketika kebijakan digerakkan cepat, terukur, dan lintas kementerian, kepercayaan pulih, ekonomi bangkit, dan rakyat kecil tidak ditinggalkan. Saat itu, pertumbuhan ekonomi minus 13,13 persen, rupiah yang sempat terperosok di kisaran Rp16.800 per dolar AS berhasil ditarik kembali menuju kisaran Rp6.550–Rp7.000, dan pertumbuhan ekonomi naik signifikan menjadi surplus 1 persen dalam waktu yang relatif singkat. Semangat yang menyatukan kebijakan menjadi sistem inilah yang perlu kita hidupkan lagi, tentu dengan alat dan sesuai tantangan zaman ini.
Pelajaran Habibie berdiri di atas tiga pilar plus satu fondasi. Pilar pertama, penyehatan jantung sistem keuangan. Pemerintah melalui BPPN menutup bank bermasalah, mengambil alih yang rapuh, dan merekapitalisasi yang layak—terapi kepercayaan agar tabungan kembali aman dan kredit mengalir. Pilar kedua, jaring pengaman sosial: program padat karya, bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, dukungan layanan dasar, dan beasiswa 4 juta anak agar sekolah tidak terputus. Kebijakan ini meredam luka sosial sekaligus menyiapkan pemulihan permintaan domestik. Dalam hal ini pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
Penulis sendiri melalui PINBUK ICMI turut menjadi pelaksana program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) Kemenaker dengan menteri Fahmi Idris dan dirjen binapenta Din Syamsuddin dalam bentuk pemagangan di Lembaga Ekonomi Produktif (LEP) yang pesertanya digaji 8 bulan untuk siap terampil dan direkrut perusahaan dan penciptaan Wirausaha Baru (WUB) melalui pelatihan dan pemberian modal kerja. Dikenalnya dan maraknya BMT yang berkembang hingga kini dan lahirnya banyak WUB saat itu di antaranya karena program tersebut.
Pilar ketiga, pemberdayaan UMKM: akses permodalan untuk koperasi, petani, dan UMKM (menyasar lebih dari 6 juta user debitur kecil) hingga ekonomi rakyat bergerak sebagai mesin pemulihan. Di bawah semuanya itu, pondasi kelembagaan ditancapkan: independensi Bank Indonesia, sehingga arah moneter kredibel dan kebijakan tak terseret tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Tujuan akhirnya jelas: kebijakan berjalan bukan karena tokoh, melainkan karena sistem.
Semangat itu kini dijahit ulang lewat Paket Ekonomi 2025. Di tangan Purbaya, paket ini bukan daftar acak, melainkan toolbox yang disetel menjadi orkestra lintas kementerian: program akselerasi pada 2025, kesinambungan ke 2026, serta fokus penyerapan kerja. Dari sisi permintaan, pemerintah memperkuat daya beli dengan magang bergaji bagi lulusan baru yang rentan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di ekosistem pariwisata dan padat karya, bantuan pangan untuk keluarga berpenghasilan rendah, serta diskon iuran jaminan sosial bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek, sopir, dan kurir. Di sisi penawaran, deregulasi dipacu lewat implementasi aturan perizinan berbasis risiko, digitalisasi tata ruang (RDTR), dan integrasi perizinan ke OSS—memangkas friksi yang selama ini membuat pelaku usaha kehabisan napas sebelum berlari.
Pemerintah juga menyiapkan program perkotaan yang menghubungkan perbaikan perumahan dengan platform pemasaran UMKM dan ekonomi gig maka hari hari ini di sosmed mulai muncul penawaran rumah dengan KPR bersubsidi yang bisa diakses pekerja sektor informal seperti driver ojol, dsb, mendorong paket pelatihan kerja yang tidak berhenti di sertifikat, melainkan berujung pada pesanan dan pendapatan, dst.
Pengungkit pembiayaan mendapat perhatian khusus. Negara memindahkan likuiditas 200 triliun ke bank milik pemerintah dengan aturan main yang terang: dana itu dipakai untuk menyalurkan kredit, terutama ke koperasi, petani dan UMKM, bukan sekadar diparkir di instrumen keuangan. Tujuannya menurunkan biaya dana, memperbaiki transmisi ke suku bunga, dan mempercepat akses permodalan produktif.
Agar tak berubah menjadi angka cantik di neraca, penyaluran diarahkan ke sektor riil dengan pelaporan berkala. Di sisi pajak, perpanjangan tarif ringan PPh Final UMKM 0,5 persen untuk beberapa tahun ke depan memberi kepastian usaha, sekaligus memantaskan UMKM naik kelas melalui pembukuan sederhana dan akses kredit berbasis data transaksi. Intinya, fiskal tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menyiapkan syarat agar usaha kecil lebih tertib, bankable, dan berdaya saing.
Rohnya sama dengan Habibie: pulihkan dan jaga kepercayaan, lalu pacu pertumbuhan. Bedanya, konteks kita kini bukan krisis moneter yang menuntut terapi gawat darurat, melainkan akselerasi dari stabilitas menuju lompatan. Karena itu, instrumen yang dipilih pun berevolusi: dari penyehatan bank dan program darurat, sekarang menjadi perizinan berbasis risiko, OSS yang terintegrasi, digitalisasi tata ruang, platform ekonomi gig (kerja singkat), dan skema magang bergaji yang menutup jurang keterampilan. Namun benang merahnya tak berubah—kebijakan harus menyentuh hidup sehari-hari sembari memperbaiki aturan main agar dunia usaha berani berekspansi.
Di titik ini saya ingin menambahkan sorotan penting: transformasi ekonomi tidak hanya tentang menggarap segmen sasaran baru (ekstensifikasi), melainkan juga mengoptimalkan segmen yang sudah ada (intensifikasi). Banyak koperasi, kelompok tani, nelayan, dan UMKM telah bertahun-tahun berjuang dengan modal sosial, jaringan anggota, dan pasar lokal yang nyata.
Kebijakan harus menyuntikkan upgrade kelembagaan bagi mereka: tata kelola yang lebih rapi, literasi keuangan dan digital, standard operating procedure yang sudah teruji dan mudah diikuti, serta sistem akuntansi digital yang membuat mereka bankable tanpa kehilangan jati diri. Di sisi pasar, pemerintah bisa menjembatani kontrak pembelian dari anchor buyers—ritel modern, hotel-restoran-kafe (Horeka), BUMN, dan belanja pemerintah—agar koperasi dan UMKM tak hanya tampil di etalase, tetapi juga menerima pesanan berulang. Di sisi pembiayaan, kredit murah perlu dibundel dengan pendampingan bisnis, bukan dibiarkan sebagai utang tanpa navigasi. Dengan intensifikasi seperti ini, kebijakan bukan hanya “menambah jumlah penerima”, melainkan mengangkat kualitas pelaku yang sudah eksis supaya produktivitas nasional naik dari dalam.
Sorotan kedua, transformasi tidak bisa dikerjakan oleh unsur struktural pemerintah saja, baik pusat maupun daerah. Kita perlu melibatkan segenap komponen rakyat/masyarakat—ormas, LSM, perguruan tinggi, komunitas profesional, bahkan diaspora—sebagai co-producer kebijakan. Koperasi yang sudah terbukti berjaya perlu dilibatkan sebagai mitra strategis pembelajaran dan kerjasama bisnis. Kampus bisa menjadi living lab yang menguji model bisnis koperasi, mengoptimalkan rantai pasok komoditas, atau merancang scorecard sederhana bagi pengurus.
Ormas dan LSM dapat berperan sebagai pengorganisasi, pengawas sosial, sekaligus jembatan ke kelompok yang sulit dijangkau birokrasi. Praktisi profesional menutup celah know-how yang tak terjawab oleh pelatihan generik. Ketika seluruh komponen bergerak dalam semangat gotong royong, kebijakan tidak hanya top-down; ia menjadi gerakan sosial-ekonomi yang hidup melaju.
Sorotan ketiga, ruang kreativitas dan inovasi bagi pelaku harus dibuka lebar. Bukan skema tunggal versi pemerintah yang serba seragam, melainkan open architecture kebijakan: matching grant untuk inovasi lokal, sandbox regulasi bagi model bisnis baru, block grant fleksibel untuk koperasi kinerja tinggi, dan kontrak berbasis hasil (outcome-based) bagi pendampingan. Dengan prinsip “tujuan jelas, cara luwes”, pelaku di lapangan—yang paham konteks budaya, geografi, dan kebiasaan setempat—bisa menyesuaikan metode yang paling efektif sesuai pengalaman dan kearifan mereka. Justru di pertemuan antara arah kebijakan nasional dan kreativitas lokal inilah lahir efisiensi dan keberlanjutan.
Sorotan keempat, adalah pemetaan dan penataan ekosistem keuangan. Tanpa itu, program baru mudah tumpang tindih bahkan saling mengkanibal. Padahal tiap lapisan pasar—Bank Umum/Syariah, BPD, PNM, BPR/BPRS, Koperasi, LKM/S, BMT, Fintech, hingga Pasar Modal ritel—punya peran berbeda yang harus jelas dan saling melengkapi. Dengan klasifikasi yang rapi, kita tahu siapa fokus di ultra mikro, siapa menopang UMKM, siapa menghubungkan ke investor besar.
Penataan ini bukan sekadar mencegah persaingan tidak sehat, tetapi memastikan semua simpul saling menguatkan dan memberdayakan. Bila diadu di pasar bebas, tentu yang besar dan kuat akan menyingkirkan yang kecil, dengan suntikan modal besar pemerintah menata dan mendorong kolaborasi untuk mengakselerasi dana ke sektor riil yang lebih luas dan partisipasi kolaborasi semua institusi keuangan. Jika ekosistem ini tertata, pertumbuhan akan lebih cepat sekaligus adil dan berkelanjutan.
Agar optimisme ini bekerja, penjaga pagar perlu ditegakkan. Likuiditas besar hanya bermakna jika benar-benar mengalir ke koperasi dan UMKM produktif. Kita membutuhkan dasbor publik yang memuat penyaluran per sektor, wilayah, suku bunga efektif, dan kualitas kredit. Jika target tak tercapai, insentif ke bank mesti disetel ulang. Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5 persen jangan dimaknai sebagai pembiaran informalitas; ia harus menjadi jembatan menuju formalisasi—pembukuan sederhana, integrasi "data transaksi" (QRIS, e-commerce, aplikasi kasir POS) sebagai dasar credit scoring yang efektif, dan kurikulum peningkatan kapasitas yang berujung pada akses pembiayaan murah.
Deregulasi perizinan harus selaras dengan audit trail digital dan pengawasan berbasis risiko di daerah, agar izin yang cepat tetap akuntabel pada aspek lingkungan, keselamatan, dan tata ruang. Dan *tim percepatan yang dibentuk pemerintah mesti punya taring: mekanisme “masalah–keputusan–waktu” yang jelas, kanal aduan pelaku usaha yang diproses mingguan, serta publikasi progres agar kepercayaan tidak sekadar dituntut, melainkan dipelihara.
Koordinasi pusat–daerah juga perlu dirapikan. RDTR, OSS, hingga pendampingan UMKM berada di lapangan pemerintah daerah; karena itu playbook teknis, pendanaan bersama, dan tolok ukur layanan harus dibuka agar kepala daerah berani mengeksekusi cepat tanpa ragu. Pada saat yang sama, policy mix fiskal–moneter perlu dikomunikasikan dengan bahasa sederhana dan konsisten. Ketika pasar memahami rambu kebijakan—apa prioritasnya, bagaimana urutannya, dan kapan evaluasinya— risk premium turun tanpa harus menguras anggaran. Komunikasi yang rapi bukan kosmetik, melainkan alat kebijakan yang menurunkan biaya modal dan mempercepat keputusan dunia usaha.
Saya optimistis karena melihat arah dan alatnya masuk akal. Sudah ada modelnya, Habibie membuktikan bahwa keberanian, kehadiran, dan penguatan institusi dapat membalikkan arus sejarah. Prabowo–Purbaya menyalakan semangat itu dalam bentuk orkestra kebijakan yang sesuai zaman: 1) stimulus yang menyentuh rakyat, 2) perizinan yang ramah pelaku usaha, 3) likuiditas yang diarahkan ke kredit/pembiayaan produktif, dan 4) ruang kreatif yang dibuka bagi pelaku di lapangan.
Ukuran suksesnya bukan di panggung peluncuran program, melainkan di pasar tradisional yang lebih ramai, bengkel dan warung yang omzetnya naik, izin usaha yang terbit lebih cepat, serta wajah-wajah keluarga yang sedikit lebih lega karena pengeluaran dapur lebih terjangkau. Jika orkestra ini terus main dalam tempo yang sama—pemerintah, dunia usaha, daerah, ormas, LSM, kampus, dan masyarakat—kita tidak hanya stabil, tetapi melesat. Koperasi dan UMKM menjadi lokomotif, anak muda menjadi energi baru, dan policy mix yang konsisten menjadi rel yang membawa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan sedang menuju lintasan yang lebih cepat dan merata. Inilah optimisme yang bekerja: bukan sekadar kata-kata, melainkan rencana yang kita kawal bersama, dengan ruang bagi kreativitas, intensifikasi, dan inovasi di setiap tingkat kehidupan ekonomi. Semoga.

 4 hours ago
6
4 hours ago
6